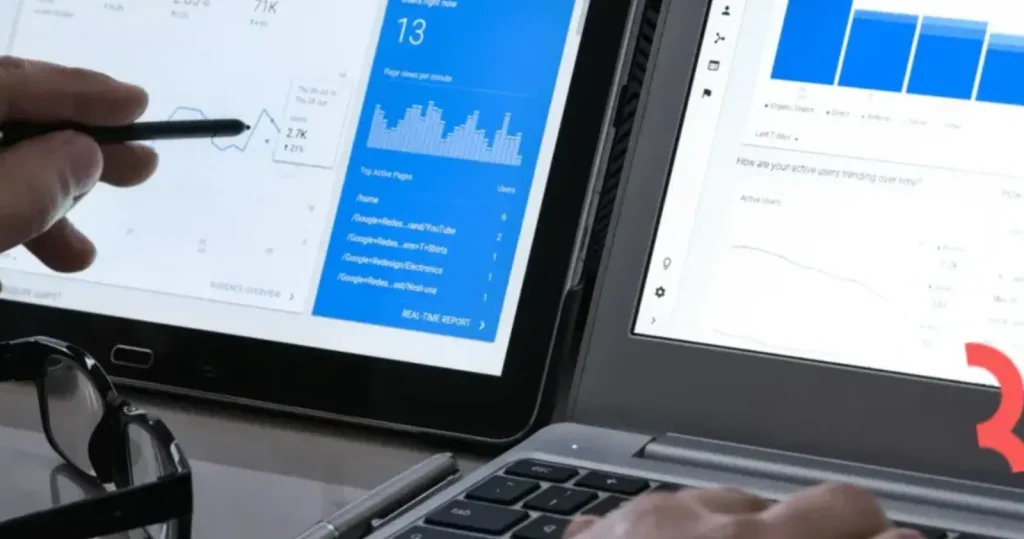Kita dulu memahami masyarakat lewat survei, sensus, wawancara, dan observasi. Metode itu masih penting—tapi sekarang ada “lapisan baru”: jejak digital yang memotret perilaku harian dalam skala besar. Inilah yang sering disebut data besar sosial: data ber-volume tinggi, cepat berubah, dan datang dari banyak sumber (platform digital, sensor kota, transaksi, mobilitas, dan seterusnya). OECD menyebut ledakan “big data” berpotensi membantu kebijakan publik, sekaligus memunculkan tantangan baru bagi tata kelola statistik dan kualitas data.
Perubahan paling besar bukan sekadar jumlah data. Yang berubah adalah cara kita bertanya dan cara kita menarik kesimpulan.
1) Dari “apa yang orang bilang” ke “apa yang orang lakukan”
Survei mengandalkan jawaban. Big data mengandalkan perilaku: orang benar-benar klik apa, bergerak ke mana, berinteraksi dengan siapa, belanja apa, jam berapa aktif.
Keuntungannya:
-
Lebih dekat ke tindakan nyata.
-
Bisa dilihat per jam/per hari, bukan nunggu laporan bulanan.
Risikonya:
-
Perilaku digital tidak selalu mewakili semua orang (yang offline jadi tak terlihat).
-
Data perilaku bisa salah dibaca tanpa konteks budaya, ekonomi, dan situasi lokal.
2) Dari statistik “lambat” ke indikator “real time”
Dalam konteks kota besar (misalnya Jakarta), data mobilitas, kepadatan area, atau permintaan layanan bisa dibaca jauh lebih cepat daripada laporan tradisional. OECD menyorot bagaimana adopsi big data membantu merespons tantangan masyarakat dengan data—tetapi juga menuntut kapasitas dan tata kelola yang kuat.
Artinya: kebijakan bisa lebih cepat “melihat” masalah. Tapi kalau indikatornya bias atau tidak stabil, kebijakan juga bisa salah arah dengan cepat.
3) Munculnya “social physics”: masyarakat dianggap bisa diprediksi
Ada gagasan yang makin populer: kalau datanya cukup besar, pola sosial bisa diprediksi seperti sistem fisika. OECD bahkan menyebut istilah “social physics” untuk menggambarkan dorongan ini—data makin “keras”, prediksi makin menggoda.
Manfaatnya nyata:
-
Prediksi penyebaran isu, panic buying, atau perubahan perilaku.
-
Deteksi dini tren kesehatan, ekonomi, dan keamanan.
Tapi ada jebakan:
-
Manusia bukan partikel. Ada nilai, emosi, dan kejutan sosial.
-
Prediksi yang “terlalu dipercaya” bisa mematikan diskusi publik dan nurani.
4) Kebijakan publik makin data-driven (dan itu bisa bagus)
World Bank sering menyorot bagaimana inovasi big data dipakai untuk pengambilan keputusan dan pembangunan, termasuk memperkaya wawasan kebijakan.
Di level praktis, big data bisa:
-
Membantu memetakan kebutuhan layanan (transportasi, kesehatan, pendidikan).
-
Mengukur dampak program secara lebih cepat.
-
Mengarahkan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Namun, World Bank juga menekankan isu rumit: privasi dan penggunaan etis big data harus ditangani serius, bukan belakangan.
5) Ilmu sosial berubah: gabungan peneliti + data scientist
Dulu, riset sosial bisa jalan dengan sampel kecil tapi dalam. Sekarang, riset sosial yang kuat sering menggabungkan:
-
metode kualitatif (makna & konteks)
-
metode kuantitatif skala besar (pola & tren)
-
Hasil idealnya: kita tidak cuma tahu “berapa banyak”, tapi juga “kenapa” dan “bagaimana”.
6) Masalah besar: bias algoritma dan echo chamber
Data besar tidak netral. AI dan sistem pencarian/feeds bisa memperkuat bias yang sudah ada. UNESCO memberi contoh dilema etis AI: sistem bisa menghasilkan bias dan mesin pencari bisa jadi echo chamber karena mengutamakan sinyal klik dan lokasi.
Efek sosialnya:
-
Polarisasi makin tajam.
-
Kelompok tertentu “tak terlihat” atau “distorikan” dalam data.
-
Kebijakan yang memakai data bias bisa ikut bias.
Skill penting di sini adalah audit bias dan validasi lintas sumber, bukan cuma “percaya dashboard”.
7) Profiling & keputusan otomatis: ketika data ikut “menentukan nasib”
Saat data besar dipakai untuk keputusan (kredit, rekrutmen, bantuan, asuransi), risikonya naik kelas. Regulator privasi menaruh perhatian khusus pada keputusan otomatis dan profiling. GDPR (Pasal 22) memberi hak agar seseorang tidak menjadi subjek keputusan yang semata-mata berbasis pemrosesan otomatis jika berdampak signifikan.
Otoritas privasi seperti ICO menjelaskan keputusan otomatis adalah keputusan tanpa keterlibatan manusia; sering berbasis profiling atau inferensi. ICO
Kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari:
-
kamu bisa “ditolak” atau “ditandai” oleh mesin,
-
tanpa tahu alasan yang masuk akal,
-
dan tanpa jalur banding yang manusiawi.
8) Etika dan privasi jadi fondasi, bukan aksesori
UNESCO menekankan prinsip-prinsip etika AI, termasuk hak privasi dan perlindungan data sepanjang siklus AI.
Dalam riset big data, UNESCO juga menyorot tantangan baru bagi etika riset dan perlunya tata kelola data yang transparan.
Kalau organisasi memakai data besar sosial, minimal harus punya:
-
tujuan yang jelas (untuk apa data dipakai)
-
minimisasi data (ambil yang perlu saja)
-
keamanan (akses terbatas, enkripsi, logging)
-
transparansi (orang tahu datanya dipakai apa)
-
akuntabilitas (ada yang bertanggung jawab, ada jalur komplain)
9) Kenapa “data besar sosial” sering bikin kita merasa diawasi
Karena garis antara “analitik agregat” dan “mengintip individu” kadang tipis—apalagi saat data digabung dari banyak sumber. Profiling (menganalisis/ memprediksi aspek seseorang, termasuk perilaku dan lokasi) adalah konsep yang dijelaskan jelas oleh otoritas privasi Eropa.
Di titik ini, masyarakat berubah bukan hanya karena “dipahami lebih baik”, tapi karena merasa dinilai.
10) Cara melihat masyarakat yang lebih sehat: gabungkan data + kemanusiaan
Big data memberi peta. Tapi peta bukan wilayah.
Supaya analisis tidak sesat, pakai 5 kebiasaan ini:
-
Tanya: datanya mewakili siapa? Siapa yang hilang dari data?
-
Pisahkan korelasi vs sebab-akibat. Banyak pola itu kebetulan yang konsisten.
-
Validasi dengan lapangan. Wawancara/observasi masih kunci.
-
Buka asumsi model. Parameter apa yang bikin hasil jadi begitu?
-
Bangun guardrail etika. Privasi, bias, dan jalur banding harus ada.
Kalau kamu sedang membangun konten pilar atau riset yang lebih luas, topik ini nyambung banget ke ranah analisis data global—karena pola sosial lokal sering dipengaruhi tren ekonomi, migrasi, teknologi, dan regulasi lintas negara.
Intinya: data besar sosial membuat masyarakat lebih “terlihat”, lebih terukur, dan kadang lebih bisa diprediksi. Tapi tanpa etika dan konteks, ia juga bisa membuat masyarakat lebih bias, lebih diawasi, dan lebih rentan diputuskan oleh mesin.